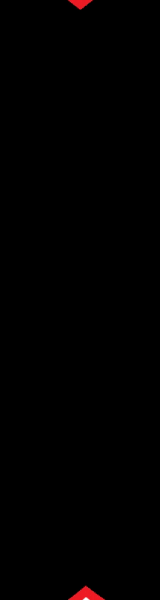Kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan, Palestina membutuhkan bantuan kita | Opini
[ad_1]
Sebagai seseorang yang tinggal di Palestina, menjalin persahabatan seumur hidup di sana, dan menghabiskan satu dekade bekerja sebagai jurnalis, saya telah melihat kehancuran yang ditinggalkan Israel dengan setiap serangan brutal terhadap orang-orang Gaza yang tak berdaya. Dampaknya terhadap warga sipil, terutama anak-anak, di wilayah yang padat penduduk itu, selalu meresahkan bagi siapa pun yang peduli untuk membaca tentang serangan Israel. Namun, saya tidak pernah membayangkan Israel akan melakukan penghancuran dan pemusnahan massal seperti yang telah dilakukannya sejak 7 Oktober.
Jumlah korban tewas resmi di Gaza kini telah mendekati 40.000 orang. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh jurnal medis The Lancet pada bulan Juni memperkirakan bahwa jumlah tersebut dapat mencapai sedikitnya 186.000 orang – atau 8 persen dari populasi Gaza. Selain itu, lebih dari 90.000 orang telah terluka, banyak di antaranya mengalami cedera yang mengancam jiwa. Mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak.
Menyaksikan penderitaan warga Palestina di Gaza sungguh menyayat hati dan saya, seperti banyak orang lainnya, merasa tidak berdaya dan bersalah.
Tak ada gambar mengejutkan tentang anak-anak Palestina yang tewas, dan tak ada laporan tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel yang berhasil mempengaruhi para pemimpin dunia untuk benar-benar melakukan sesuatu untuk menghentikan Israel. Protes dan permohonan tampaknya tidak berhasil meyakinkan pemerintah untuk bertindak. Ketidakpedulian total terhadap kehidupan warga Palestina oleh para pemimpin kita sungguh membuat frustrasi.
Sementara itu, saya – seperti jutaan orang lain di Barat – tidak khawatir tentang perang atau pendudukan dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya merasa bersalah karena saya aman di sini, di Amerika Serikat, sementara pemerintah saya mendanai dan mempersenjatai Israel yang melakukan genosida.
Melihat gambar dan video orang tua yang mengambil anak-anak mereka yang meninggal dari reruntuhan rumah dan sekolah sungguh menyayat hati. Saya memiliki seorang putri kecil dan saya tidak dapat membayangkan ketidakberdayaan dan kemarahan yang akan saya rasakan jika saya adalah orang tua Palestina di Gaza.
Saya telah berusaha sekuat tenaga untuk melawan kelumpuhan akibat ketidakberdayaan dan rasa bersalah ini. Saya telah menghubungi teman-teman di Tepi Barat secara berkala dan mencoba membantu semampu saya. Melalui mereka, saya sering mendengar kisah-kisah memilukan tentang orang-orang yang mereka kenal di Gaza.
Namun, ada satu cerita yang membekas dalam ingatan saya. Seorang teman lama di Ramallah bercerita tentang Ahmed*, seorang ayah dari Gaza, yang terjebak di Tepi Barat yang diduduki setelah 7 Oktober, sementara seluruh keluarganya tetap tinggal di Jalur Gaza. Ahmed datang ke Tepi Barat untuk berobat atas masalah kesehatan yang dideritanya. Ketika perang dimulai, ia ingin kembali tetapi tidak menemukan jalan.
Ia terus-menerus merasakan sakit karena perpisahan dan ketakutan bahwa sesuatu akan terjadi pada keluarganya. Tekanan karena tidak dapat melindungi istri dan anak-anaknya memperburuk kondisi kesehatannya.
Ahmed pernah mendengar tentang kampanye GoFundMe yang menggalang dana untuk membantu mengevakuasi keluarga Palestina dari Gaza dengan membayar biaya yang diminta oleh pialang Mesir – sekitar $5.000 per orang. Ada beberapa kisah sukses penggalangan dana yang memberinya harapan bahwa ia juga bisa menyelamatkan orang-orang yang dicintainya.
Ahmed menyampaikan ide tersebut kepada salah seorang teman saya di Tepi Barat, yang mengira saya dapat membantu menyiapkannya karena saya memiliki rekening bank yang memenuhi syarat untuk menyiapkan kampanye GoFundMe. Saya sangat bersedia membantu. Saya menyiapkan kampanye tersebut pada bulan April dan telah berusaha menggalang dana sejak saat itu.
Saya telah berbicara dengan Ahmed dan menghubungi anak-anaknya di Gaza. Kisah mereka yang menyedihkan telah membuat saya semakin termotivasi untuk melakukan apa pun yang saya bisa untuk menyukseskan kampanye ini.
Putra Ahmed yang berusia 20 tahun, Karam, memberi saya kisah terperinci tentang kengerian yang ia dan saudara-saudaranya – Mahmoud, 18; Amneh, 15; Saja, 12; Zaina, 9 dan Mohammed, 6 – dan ibu serta bibi mereka – Aman dan Zaina – telah lalui. Pada awal invasi Israel ke Gaza, mereka harus meninggalkan rumah mereka di distrik Athe at-Twam, utara Kota Gaza dengan hampir tidak ada apa-apa selain pakaian di badan mereka, karena rumah itu dibom tanpa pandang bulu. Mereka pertama-tama menuju ke rumah paman mereka di Tal al-Hawa di selatan Kota Gaza, kemudian ke saudara lain di kamp pengungsi Jabalia. Di sana, pada bulan Desember, rumah tempat mereka tinggal dibom saat mereka semua berada di dalam.
“Dinding rumah mulai runtuh di sekitar kami, dengan serpihan beterbangan ke segala arah,” Karam menjelaskan. “Saat itu benar-benar kacau dan hancur.”
Kaki kanan Karam patah dan ia mengalami luka bakar tingkat tiga akibat pengeboman tersebut. Mohamad yang berusia enam tahun mengalami luka bakar di wajah dan tangan. Anggota keluarga lainnya juga menderita luka bakar. Akibat serangan Israel terhadap rumah sakit, mereka tidak bisa mendapatkan perawatan medis yang layak. Keluarga tersebut mendengar bahwa ada rumah sakit yang berfungsi di Deir el-Balah, jadi saat itulah mereka memutuskan untuk memulai perjalanan ke selatan menuju Gaza tengah untuk mencari perawatan medis.
Karam menggambarkan pemandangan mengerikan yang mereka saksikan saat mereka melakukan perjalanan ke selatan pada hari terakhir “koridor jalur aman” Israel bagi warga Palestina yang ingin mengungsi dari Gaza utara. Tentu saja, itu sama sekali bukan jalur aman.
“Jalanan dipenuhi mayat-mayat yang terbakar dan ambulans yang terbakar … Saya melihat seluruh keluarga terbunuh di dalam mobil mereka,” kata Karam. “Dan dalam perjalanan, kapal-kapal militer Israel terus menembaki kami.”
Keluarga tersebut sampai di Deir el-Balah di Gaza tengah di mana mereka mendirikan tenda darurat.
“Ukuran tenda itu lima meter kali empat meter. Anak-anak perempuan tidur bersebelahan, ibu dan adik laki-laki saya tidur bersebelahan. Saya tidur di pintu karena tempatnya sempit,” kata Karam.
Karam menceritakan bahwa mereka tidak punya apa pun untuk tidur atau menutupi diri saat pertama kali tiba di sana dan cuaca masih dingin. Di musim panas, kondisi memburuk, karena panas, lalat, dan nyamuk menjadi tak tertahankan.
Karam dan saudaranya masih menderita luka-luka mereka, karena mereka tidak bisa mendapatkan obat yang tepat untuk mengobati luka bakar tingkat tiga mereka. Adik perempuan mereka yang termuda, Zaina, sekarang menderita PTSD, dan panik sampai kejang-kejang ketika mendengar pesawat Israel terbang di atas mereka – terutama ketika pesawat itu terbang rendah dan mengeluarkan bunyi sonik. Ketiga anak laki-laki itu tertular hepatitis dari air kotor dan mata serta kulit mereka mulai menguning. Tidak ada pengobatan untuk penyakit ini di Gaza.
Keluarga tersebut sangat bergantung pada makanan kaleng dari organisasi bantuan untuk bertahan hidup. Makanan segar terlalu mahal dan kayu bakar semakin tidak terjangkau. Bahan bakar untuk memasak hampir tidak ada lagi.
Karam dan saudara-saudaranya menghabiskan sebagian besar hari untuk mencari air, baik air laut maupun air tawar – yang terakhir sangat sulit ditemukan.
Keluarga itu hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa tenda mereka akan dibom.
“Mereka tidak peduli dengan anak-anak atau wanita, kematian adalah hal yang paling mudah di Gaza,” kata Karam. “Kami telah mencapai titik di mana setiap saat Anda dapat menemukan bagian tubuh apa pun di sebuah apartemen.”
Keluarga itu telah melalui begitu banyak hal sehingga ketika saya berbicara dengan mereka, keputusasaan itu terasa nyata. Dengan semua yang telah terjadi sejak Oktober, sulit untuk merasa berharap. Namun, meskipun harapan terasa mustahil mengingat kejahatan mengerikan yang terus berlanjut terhadap warga Palestina yang tidak bersalah, itu benar-benar satu-satunya jalan ke depan.
Perbatasan Rafah telah ditutup sejak pasukan Israel menyerangnya pada bulan Mei. Hal itu menghentikan evakuasi yang ditengahi Mesir untuk saat ini. Keluarga Ahmed berharap untuk mengungsi setelah perbatasan dibuka kembali, terlepas dari apakah gencatan senjata terjadi atau tidak. Itu karena rumah dan semua yang mereka miliki hancur, dan masalah medis yang mereka alami tidak dapat ditangani dengan baik di Gaza. Mereka juga ingin bersatu kembali dengan Ahmed sesegera mungkin. Jika mereka tidak dapat mengungsi, uang itu akan digunakan untuk perawatan medis apa pun yang dapat mereka peroleh dan untuk membangun kembali kehidupan mereka di Gaza.
Saya harus percaya bahwa mengambil tindakan, tindakan apa pun, dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tidak seorang pun dari kita secara individu dapat menghentikan genosida Israel, tetapi masing-masing dari kita secara individu dapat membuat perbedaan besar bagi keluarga Palestina seperti keluarga Ahmad. Kampanye penggalangan dana – meskipun memakan waktu lama – memberi keluarga-keluarga ini harapan. Hal itu membuktikan kepada mereka bahwa seluruh dunia peduli, bahwa kehidupan warga Palestina penting.
*Nama ayah keluarga tersebut telah diubah untuk melindungi identitasnya, karena warga Palestina dari Gaza telah menjadi sasaran pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan belum tentu mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.
[ad_2]
Sumber: aljazeera.com