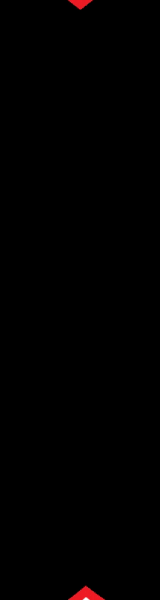Olivia Gatwood Terbit 9 Juli Dari The Dial Press
[ad_1]
Sempurna untuk hari-hari musim panas yang terik hingga malam yang lembap, Olivia Gatwood Siapapun Kamu, Sayang (terbit 9 Juli dari The Dial Press) terasa seperti mimpi buruk di era AI. Cerita ini mengikuti kehidupan dua orang yang tidak diduga, Mitty dan Bethel, yang telah tinggal bersama di sebuah rumah reyot di pantai Santa Cruz, California selama satu dekade. Ketika pendiri perusahaan teknologi Sebastian dan pacarnya Lena pindah ke rumah raksasa yang sangat modern di sebelahnya, Mitty pun tertarik ke dalam kehidupan mereka.
Namun seiring berjalannya waktu, ingatan Lena yang tidak dapat diandalkan dan perilaku Sebastian yang suka mengontrol mulai terungkap. Semakin dekat Lena dan Mitty, mereka semakin terpaksa menghadapi masa lalu dan rahasia yang tersembunyi di balik permukaan.
Di bawah, intip dunia mereka melalui tirai, dalam kutipan eksklusif yang dibagikan kepada ORANG.
Pers Panggilan
Di tengah malam, hamparan properti tepi pantai yang jarang dihuni di sepanjang Jalan Pantai Perut Buncit menyerupai deretan gigi yang menganga. Setidaknya inilah yang selalu dibayangkan Mitty. Jika seorang pelaut di lepas pantai terjaga dan melihat ke luar jendela kabinnya, saat dia sedang melakukan perjalanan melalui Teluk Monterey, khususnya di sepanjang pantai Santa Cruz, dan bahkan lebih khusus lagi Pantai Negara Bagian New Brighton, dia mungkin memperhatikan kantong hitam tempat kapal-kapal kosong berada. rumah-rumah duduk, dipecah oleh cahaya hangat dari ruang tamu yang terang, dan mungkin teringat akan mulut bergetah seorang anak.
Selama bertahun-tahun, sejumlah rumah ini telah dijual dan diubah menjadi persewaan liburan dan penginapan musim panas, menjadikan Mitty dan Bethel sebagai penghuni tetap terakhir yang tersisa di lingkungan tersebut. Tentu saja mereka menyesali perubahan ini. Bisa dibilang, sebagai satu-satunya warga setempat, protes ini sudah menjadi tanggung jawab mereka. Namun tetap saja, ada sebagian kecil dari Mitty yang senang dengan kejutan dari para penyewa bergulir tersebut. Ketika dia keluar untuk berjalan-jalan di malam hari, dia gembira dengan ketidakmampuannya memprediksi properti mana yang akan sibuk, malam transparan mana yang akan dia saksikan, tetangga mana yang akan dia kenal tanpa pernah berbicara dengan mereka. .
Di luar, pepohonan eucalyptus berbisik. Pasir mengepal di bawah kaki telanjangnya. Rumah-rumah tersebut berdiri di atas panggung, setinggi setidaknya 10 kaki dari permukaan tanah. Saat dia berjalan, orang asing terus tinggal di atasnya. Sepasang suami istri paruh baya — dia berasumsi bahwa mereka berasal dari Berkeley, dan memang sering kali demikian — meninggalkan rumah mereka yang diselimuti kabut untuk akhir pekan di pantai yang diselimuti kabut. Wanita itu memarut tumitnya dengan batu apung sementara pria membalik-balik katalog digital film di layar datar, nampaknya tidak peduli dengan tubuh istrinya yang tertumpah.
Di rumah berikutnya, seorang ayah muda dengan kelopak mata berat meminta izin untuk meninggalkan meja makan, sementara seorang wanita menyelipkan sendok ke mulut balita mereka. Ia berdiri di wastafel dapur, melihat ke luar. Ia tampak seperti sedang mengagumi pemandangan, menikmati momen singkat kesendirian ini. Namun Mitty tahu dari rumahnya sendiri bahwa pada jam seperti ini, tidak ada pemandangan. Yang dapat Anda lihat hanyalah pantulan diri Anda sendiri, yang menatap balik.
Tiga rumah berikutnya kosong; dia bergegas melewati celah itu. Tidak dapat melihat apa yang ada di balik jendela yang sunyi dan murung itu selalu membuatnya gelisah. Rumah yang dia tinggali bersama Bethel adalah yang terakhir di tanah itu, pos terdepan terakhir kehidupan sebelum pasir menghilang dan meletus menjadi tebing terjal, membuat tempat tinggal mereka yang kolot terasa seperti tempat berlindung. Bahkan dari jauh, dia dapat melihat Bethel di jendela saat dia mengeringkan piring makan malam mereka. Rambutnya sewarna tiram, matanya lebar seperti katak pohon, lengan bawahnya yang rapuh disiram bintik matahari yang menjalar ke seluruh jari-jarinya yang kurus kering memainkan piano. Di belakangnya, dapur dihiasi dengan kertas dinding bermotif aprikot paisley yang disematkan di tengah langit-langit oleh lampu gantung plastik.
Mitty berhenti sejenak dari tempat mereka dan menatap rumah di sebelahnya, sebuah bangunan yang luas dan geometris; begitu banyak kaca sehingga hampir tampak tidak memiliki dinding. Dia dan Bethel menyebutnya “rumah boneka”, sambil bercanda bahwa sepertinya seorang anak dapat langsung masuk ke dalam dan mengatur ulang perabotannya. Namun selama lima tahun terakhir, rumah tersebut tetap kosong. Saking kosongnya, hingga Mitty hampir lupa kalau ruangan itu dulunya sama seperti milik mereka, berpanel kayu dan miring. Rumah itu dimiliki oleh sepasang profesor eksentrik yang dikirim ke panti jompo oleh anak-anak mereka.
Dia rindu melihat pasangan tua itu membawa meja makan panjang mereka ke pantai tempat orang-orang tua beruban dan mahasiswa berkumpul di sekitarnya, minum-minum dan berdebat, hingga larut malam. Dia rindu ajakan mereka yang terus-menerus untuk bergabung, berteriak-teriak di jendela Bethel yang terbuka. Dia rindu membiarkan pintu-pintu Prancis di balkonnya terbuka sedikit dan tertidur karena mendengar suara mereka, suara tawa yang menggelegar yang terus berlanjut hingga fajar.
Ketika mereka pergi, rumah itu langsung diratakan dengan buldoser, dan di tempatnya datanglah orang-orang berjas dan helm, menunjuk ke kamar-kamar imajiner dan meneriakkan luas persegi. Mitty dan Bethel menyaksikan rumah boneka itu terwujud dari kursi depan ruang tamu mereka, mengumpat setiap dinding kaca baru yang dikirim ke lokasi kerja, ternganga ngeri saat truk semen memenuhi jalan setapak dengan adonan abu-abu. Tapi ini bukan renovasi seperti rumah-rumah lain di ujung pantai, beberapa renovasi tergesa-gesa untuk disewa seharga $500 per malam. Pengembang tak berwajah apa pun yang ada di balik rumah boneka itu sedang membangun tempat tinggal penuh waktu, rumah selamanya, mempersiapkan eksodus teknologi yang akan datang dari San Francisco. Di sanalah rumah itu telah teronggok, kosong, dan dipasarkan selama setengah dekade. Sepatu kaca yang menunggu kaki yang sempurna.
Sampai sekarang.
Mitty melihat truk-truk pindahan tiba pagi itu saat ia bersiap berangkat kerja. Ia sempat mempertimbangkan untuk berkeliaran di sana untuk melihat apa yang bisa ia pelajari tentang tetangga barunya berdasarkan harta benda mereka. Namun, ia memilih untuk menunggu dan mengamati dari bunker tersembunyi di pantai yang gelap ini, saat ia tahu perabotan pasti sudah diturunkan dan ditata; semuanya sudah pada tempatnya. Tentu saja, mengingat mereka sudah tinggal di sini selama 12 jam, rumah itu masih setengah kosong dan berantakan, yang membuatnya tidak puas. Tumpukan buku-buku seni yang berat dipajang sementara di meja makan, pernak-pernik yang baru saja dibuka dari kehidupan yang sering dilalui — seekor gajah kayu dari, ia bayangkan, Namibia; topi anyaman dari Peru — menghiasi rak-rak pinus mereka yang telanjang.
Dia heran bagaimana seseorang bisa mulai melengkapi rumah yang begitu besar, dan dengan begitu sedikit karakter. Mungkin itu sebabnya mereka semua tetap setia pada gaya hidup minimalis, berdasarkan fakta bahwa gaya hidup ini tidak terlalu sulit.
Ketika Mitty masih kecil, dia menghabiskan Natal dengan berkeliling di lingkungan kaya di seluruh kota, mengagumi pertunjukan mewah mereka. Rusa kutub animatronik dan Santas yang melambai-lambai, lagu-lagu liburan berkumandang di atas generator yang menggeram. Tapi sungguh, bagian dalam rumahlah yang paling membuatnya penasaran. Dia bertanya-tanya mengapa keluarga kaya sepertinya selalu melupakan tirai. Sungguh berani, pikirnya, membangun interior yang begitu mewah dan kemudian memamerkannya kepada setiap orang asing yang lewat.
Mitty mengamati ruangan terang dan kosong di rumah itu, aura keheningan murni terpancar di balik kaca kedap suara. Dia sedang menunggu sesuatu di dalam untuk bergerak. Tapi stok rumahnya tetap utuh, seperti ruang pamer di department store.
Saat dia hampir kehilangan minat, sebuah lampu menyala di jendela atas. Dia melihat seseorang mondar-mandir, terdiam menjadi siluet di balik tirai tipis, menghilang ke salah satu sisi jendela, lalu berbalik dan menyeberang lagi. Itu adalah seorang wanita – kepala kecil dengan kuncir kuda yang ramping, pendulum gugup – yang bergerak melintasi ruangan. Setelah hampir selusin putaran, dia menghilang dari pandangan. Mitty menunggu, ketegangan membeku di perutnya. Namun meski wanita itu tidak ada, cahaya di ruangan itu tetap ada. Air pasang naik, dan busa putih menelan pergelangan kaki Mitty, mendorongnya kembali ke dunia sekitarnya. Dia bergulat dengan rumput laut yang terdampar di kakinya dan mulai berjalan pulang.
Saat dia berjalan, sesekali berhenti untuk melihat kembali ke jendela yang masih terang, dia tidak bisa tidak memikirkan kebun binatang yang dulu dia kunjungi bersama ibunya. Betapa terpesonanya dia oleh kucing-kucing besar yang menyelinap dari satu sisi kandang ke sisi yang lain, tulang belikat bergerak di kulit mereka seperti kepalan tangan yang meregangkan adonan pizza. Dia ingat bau napas ibunya, yang asam karena kopi, saat dia membungkuk di samping telinga Mitty dan berbisik, Mereka hanya berjalan seperti itu di penangkaran, ketika mereka merencanakan cara untuk melarikan diri.
Saat itu minggu kedua bulan Agustus, akhir musim panas yang berangin, dan kertas itu dipenuhi foto empat anak laki-laki, hampir mencapai titik puncak kedewasaan, mata mereka basah dan hitam seperti buah zaitun. Semua orang membicarakannya – dalam privasi rumah mereka sendiri, tentu saja, halaman belakang rumah mereka sendiri – sementara mereka menanam bibit kembang kol dan kubis Brussel ke dalam tanah yang baru digaruk. Jika Mitty peduli untuk mengetahui kejadian di sekitar kota, dia pasti sudah mendengar desas-desus tentang insinyur teknologi yang diculik oleh empat pekerja magangnya yang kurus dan ditembak di Pegunungan Santa Cruz. Namun sebaliknya, dia malah disantap oleh sederet kue gemuk di balik kaca kotak kue di depannya, di supermarket luar kota.
Saat ini, dia dan Bethel telah menjadi teman serumah selama 10 tahun, hampir sepertiga hidup Mitty. Ini pertama kalinya salah satu hari jadi mereka terasa seperti sebuah tonggak sejarah nyata, satu dekade hidup berdampingan. Namun ketika dia memikirkan fakta bahwa Bethel berusia 79 tahun, dan bahwa sebagian besar waktunya di bumi terjadi jauh sebelum Mitty lahir, tahun-tahun mereka bersama terasa begitu singkat, begitu tidak penting, sehingga Mitty mulai bertanya-tanya apakah hal itu patut untuk dicatat.
Dia memperdebatkan hal ini dengan dirinya sendiri setiap tahun, bertanya-tanya apakah tradisi itu ada artinya bagi Bethel, yang sudah tidak menyukai banyak hal yang bersifat sentimental. Apakah dia akan menyadari jika Mitty membeli sesuatu yang berbeda, atau kembali dengan tangan kosong tanpa pemberitahuan? Pada akhirnya, Mitty selalu memutuskan bahwa, terlepas dari apakah Bethel menemukan makna dalam ritual tersebut, kue — yang berupa wortel — adalah sebuah persembahan, suatu tindakan syukur.
Dia menekankan jarinya ke kaca. “Yang itu.” Pria itu mengeluarkan makanan penutup kecil dan menyimpannya di dalam kotak. “Kamu tidak ingin ada tulisan apa pun di situ?” Mitty berpikir sejenak, membayangkan semua hal yang ingin ia katakan kepada Bethel.
Terima kasih telah menyelamatkanku. Persetan denganmu karena telah menahanku. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Dari buku SIAPAPUN KAMU, MADU oleh Olivia Gatwood. Hak Cipta © 2024 oleh Olivia Gatwood. Diterbitkan oleh The Dial Press, sebuah cetakan dari Random House, sebuah divisi dari Penguin Random House LLC.
Siapapun Kamu Sayang karya Olivia Gatwood terbit pada tanggal 9 Juli dan tersedia untuk dipesan sekarang, di mana pun buku dijual.
[ad_2]
Sumber: people-com

:max_bytes(150000):strip_icc():focal(749x0:751x2)/Whoever-You-Are-Honey-Book-Olivia-Gatwood-062824-c6a0088bfed64182956f43d4b9ee1e10.jpg)