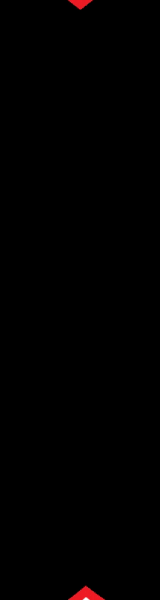Memasak di Gaza sekarang menjadi urusan beracun | Konflik Israel-Palestina
[ad_1]
Di Gaza, kami memiliki suara ketakutan dan kecemasan. Kita mengenal mereka dengan sangat baik: dengung drone mata -mata di atas kepala, ambulans berteriak melalui jalan -jalan sempit, deru pesawat militer, guntur bom, tangisan orang yang terperangkap di bawah puing -puing dan sekarang suara baru: dentang tajam silinder gas kosong.
Kami dulu tahu betul klik kecil pembakar kompor gas mulai – percikan kecil itu pada awal hari yang berarti makanan panas atau secangkir teh akan datang. Sekarang, suara itu hilang, digantikan oleh dentang hampa kekosongan.
Kami menggunakan setetes gas memasak terakhir kami di tengah Ramadhan. Seperti semua keluarga lain di Gaza, kami beralih ke kayu bakar. Saya ingat ibu saya berkata, “Mulai hari ini, kita bahkan tidak bisa membuat secangkir teh untuk Suhoor.”
Itu karena menyalakan api, bahkan memiliki sekejap cahaya di malam hari dapat menarik drone atau quadcopter, menghasilkan serangan udara atau rentetan peluru. Kami tidak tahu mengapa cahaya di malam hari ditargetkan, tetapi kami tahu kami tidak memiliki hak untuk bertanya.
Jadi kami makan makanan dingin untuk Suhoor dan menyelamatkan api untuk Iftar.
Setelah toko roti ditutup karena kekurangan gas bulan lalu, Reliance on Fire meningkat – tidak hanya untuk keluarga kami tetapi untuk semua orang. Banyak orang membangun oven tanah liat darurat atau kebakaran di gang atau di antara tenda untuk memanggang roti.
Asap hitam tebal menggantung berat di udara – bukan asap kematian akibat rudal, tetapi asap kehidupan yang membunuh kita perlahan.
Setiap pagi, kita bangun batuk – bukan batuk yang lewat, tetapi batuk yang dalam, gigih, tersedak yang mengguncang di dada kita.
Kemudian, saudara laki -laki saya dan saya berjalan ke tepi lingkungan kami, di mana seorang pria menjual kayu dari belakang gerobak. Dia mengumpulkannya dari bangunan yang dibom, pohon tumbang, furnitur patah, dan reruntuhan rumah dan sekolah.
Kami membawa kembali apa pun yang bisa dilakukan oleh tubuh kami yang lemah dan beralih ke penderitaan berikutnya: membakar kayu. Ini tidak mudah. Ini menuntut berjam -jam memotong dan memecahkan kayu dan bernapas dalam debu. Ayah kami, meskipun menderita sesak napas, bersikeras membantu. Keras kepalanya ini telah menjadi sumber argumen harian, terutama antara dia dan saudara lelaki saya.
Saat kita menyalakan api, mata kita menjadi merah karena asap, tenggorokan kita menyengat. Batuk semakin meningkat.
Kayu bakar menjadi sangat mahal. Sebelum perang, kami akan membayar satu dolar seharga delapan kilo, tetapi sekarang Anda hanya dapat membeli satu kilo – atau bahkan lebih sedikit – untuk harga itu.
Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk menebang pohon mereka sendiri. Hias kehijauan di lingkungan kami telah menghilang. Banyak tetangga kami sudah mulai menebang pohon yang tumbuh di halaman mereka. Bahkan kami telah mulai menggunakan cabang dari pohon zaitun kami – pohon yang sama yang tidak pernah kami berani sentuh ketika kami masih muda, takut bahwa mengganggu itu akan menyebabkan bunga jatuh dan menghasilkan lebih sedikit zaitun.
Keluarga yang tidak memiliki pohon untuk dipotong telah beralih ke plastik, karet, dan sampah yang terbakar – apa pun yang akan terbakar. Tetapi membakar bahan -bahan ini melepaskan asap beracun, meracuni udara yang mereka hirup dan merembes ke dalam makanan yang mereka masak. Rasa plastik melekat pada setiap gigitan, mengubah setiap makanan menjadi risiko kesehatan.
Paparan asap ini konstan dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang parah dan penyakit kronis dan bahkan menyebabkan penyakit yang mengancam jiwa seperti kanker. Namun, pilihan apa yang dimiliki orang? Tanpa api, tidak ada makanan.
Ada sesuatu yang sangat kejam tentang transformasi dapur – dari simbol keluarga dan keramahtamahan menjadi zona beracun. Api yang dulu berarti kehangatan sekarang membakar paru -paru dan mata kita. Makanan yang dimasak hampir tidak bisa disebut itu: sup dari lentil; Roti dari tepung yang terinfestasi atau tepung yang dicampur dengan pasir. Kegembiraan menyiapkan makanan telah digantikan oleh ketakutan, rasa sakit dan kelelahan.
Kurangnya gas memasak ini telah melakukan lebih dari sekadar melumpuhkan akses kami ke makanan – ia telah membongkar ritual yang menyatukan keluarga. Makanan bukan lagi waktu untuk berkumpul dan menikmati waktu keluarga tetapi waktu untuk bertahan. Waktu untuk batuk. Waktu untuk berdoa agar api hari ini tidak membuat seseorang terlalu sakit.
Jika bom tidak membunuh kita, kita menghadapi kematian yang lebih lambat: tenang, beracun dan sama lemahnya.
Ini Gaza hari ini.
Tempat di mana bertahan hidup berarti menghirup racun hanya untuk minum teh di pagi hari.
Tempat di mana kayu bakar menjadi lebih berharga daripada emas.
Tempat di mana bahkan tindakan makan yang sederhana telah dipersenjatai.
Namun, kami terbakar.
Kami batuk.
Kami terus berjalan.
Pilihan lain apa yang kita miliki?
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak selalu mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.
(Tagstotranslate) Pendapat (T) Konflik Israel-Palestina (T) Israel (T) Timur Tengah (T) Palestina
[ad_2]
Sumber: aljazeera.com