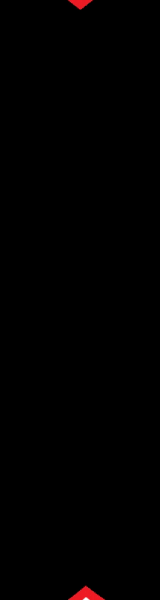Mati kelaparan sama menakutkannya dengan perang bagi pengungsi Sudan
[ad_1]
Adre, Chad – Di bawah terik matahari, Awatef Adam Mohamed menemukan perlindungan di luar perbatasan gurun yang rapuh antara Sudan dan Chad.
Dia tiba pada tanggal 8 Juni, bergabung dengan puluhan ribu warga sipil yang melarikan diri dari kengerian perang yang terjadi di wilayah Darfur, Sudan barat.
Namun baru-baru ini, krisis lain mulai mendorong orang keluar dari Sudan, kelaparan besar yang mengancam jutaan orang.
Mencari keselamatan, mencari rezeki
Sejak perebutan kekuasaan antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter yang meletus menjadi perang saudara pada tanggal 15 April 2023, kedua belah pihak telah menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis yang menghancurkan.
Sekitar 10 juta orang kehilangan tempat tinggal – angka tertinggi di dunia – dan kondisi seperti kelaparan sedang terjadi di seluruh negeri.
Sekitar 756.000 orang menghadapi “tingkat bencana kelaparan” dan 25,6 juta orang lainnya menghadapi kekurangan pangan akut, menurut Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu, skala tingkat kelaparan PBB.
Akibatnya, banyak orang yang berpindah-pindah, mencari keamanan fisik dan makanan yang cukup untuk menopang kehidupan, dan lebih dari 600.000 orang berakhir di Chad, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).
Banyak di antara mereka yang terpaksa bertahan hidup dan bergantung pada bantuan pangan dari Program Pangan Dunia (WFP).

Namun, kurangnya dana telah memaksa WFP untuk mengurangi bantuan makanan, mengurangi kalori harian pengungsi hampir 20 persen selama dua bulan terakhir, menurut Vanessa Boi, petugas darurat WFP di Chad.
Dengan hanya 19 persen permintaan pendanaan WFP yang dipenuhi oleh negara-negara donor dan semakin banyak pengungsi yang menyeberang ke Chad dari Darfur setiap hari, badan PBB tersebut mungkin harus semakin mengurangi bantuan makanan untuk setiap pengungsi.
“Kami telah melihat dampak dari pengurangan ini karena semakin banyak orang yang mengalami kekurangan gizi,” kata Boi.
Malnutrisi terjadi ketika tubuh manusia kekurangan nutrisi penting, bukan hanya kalori.
Namun para pengungsi terkadang tidak punya pilihan selain menukar jatah WFP mereka – yang dirancang untuk menyediakan protein, lemak dan karbohidrat dalam persentase tertentu – dengan makanan yang kurang bergizi namun lebih besar sehingga dapat mengisi perut beberapa hari lebih lama.
Omima Musa, 27, menukar paket makanannya dengan nasi putih di pasar agar dia bisa memberi makan bayinya dan dua anaknya lainnya tiga kali sehari untuk waktu yang lebih lama, jelasnya sambil menggendong bayinya dengan lembut dalam pelukannya.
Namun meskipun bayi perempuan Omima tidak terlalu lapar, ia mengalami kekurangan gizi, yang membuatnya rentan terhadap penyakit – seperti malaria.
Musa Maman – yang mengawasi dan memantau kegiatan medis untuk Doctors Without Borders, yang dikenal dengan inisial Perancis MSF – mengatakan musim hujan, yang merupakan musim utama malaria, telah dimulai dan akan berlangsung setidaknya dua bulan lagi.
“Kita akan melihat peningkatan penyakit malaria. Agustus adalah bulan terburuk,” kata Musa kepada Al Jazeera.
Trauma, ketidakpastian
Anak-anak Awatef yang berusia 27 tahun juga mengalami kekurangan gizi – itulah sebabnya dia, seperti banyak warga Darfur lainnya, menggunakan satu-satunya alat transportasi yang tersedia dan berjalan bermil-mil ke bagian timur Chad.
Setidaknya sekarang sudah aman dari kekerasan, wanita suku Masalit itu berdiri di bawah naungan tembok sambil memandang ke dunia luar, mengenakan thobe warna-warni yang kontras dengan lingkaran hitam di bawah matanya.
Suku Masalit adalah salah satu suku terbesar di Darfur dan lebih banyak menetap serta fokus pada pertanian, sehingga mereka disebut sebagai “non-Arab”. RSF dan sekutunya sering menyerang suku tersebut.
Awatef menggendong bayinya, terbungkus selendang merah, dan keempat anaknya yang lain berkerumun, lesu.
Suaminya menghilang ketika RSF dan milisi nomaden sekutunya (umumnya disebut sebagai orang Arab) menyerbu desa Masalit di Darfur Barat beberapa bulan lalu, dengan tujuan membunuh laki-laki dan remaja laki-laki.
Dua saudara laki-lakinya terbunuh di depannya dalam serangan itu.
“Mereka menjadi martir di dalam rumah,” katanya tanpa basa-basi, tidak membahas bagaimana mereka dibunuh. “Saya melihat mereka dibunuh.”
Setelah serangan itu, Awatef berjuang untuk memberi makan dirinya dan anak-anaknya, sehingga mendorongnya untuk datang ke Chad bagian timur.
Di sana mereka bergabung dengan banyak perempuan dan anak-anak yang berkerumun di gurun yang panas, menunggu untuk mendaftar ke kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk mendapatkan makanan dan perawatan medis.
Bantuan yang dibatasi, menimbulkan ketegangan
Kelompok hak asasi manusia mengatakan RSF dan tentara menciptakan krisis pangan di Sudan.
Yang pertama telah menjarah kota-kota dan pasar-pasar serta merusak hasil panen dengan menyerang dan mengusir para petani, sementara yang terakhir telah membatasi kelompok-kelompok bantuan untuk menjangkau populasi yang terkepung di wilayah-wilayah yang dikuasai RSF.
Pada bulan Maret, tentara Sudan menolak izin kelompok bantuan untuk mengirimkan makanan melintasi perbatasan Chad ke Darfur Barat, dengan alasan keamanan, dan mengatakan bahwa perbatasan tersebut telah digunakan untuk menyediakan senjata kepada RSF.
Tentara kemudian menyetujui pengiriman makanan melalui Tina, Chad, yang berbatasan dengan Darfur Utara, di mana tentara dan pasukan RSF berada. Namun hal itu tidak membantu Darfur Barat, tempat ratusan ribu orang berjuang untuk mendapatkan makanan, yang mungkin menyebabkan meningkatnya pendatang baru ke Chad, menurut Boi.
“(WFP) tidak melakukan distribusi di sisi lain – karena aksesnya sangat sulit – sehingga (pengungsi) datang ke (Chad) karena mereka tahu ada kemungkinan untuk mendapatkan akses terhadap bantuan,” katanya.
RSF muncul dari milisi suku Arab yang didukung pemerintah yang dikenal sebagai “Janjaweed” yang berperang di Khartoum melawan pemberontakan di Darfur. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang selama perang Darfur, yang dimulai pada tahun 2003 dan secara resmi berakhir dengan perjanjian damai pada tahun 2020.
Dalam kampanye yang lebih luas untuk menumpas kelompok bersenjata non-Arab yang memberontak terhadap marginalisasi komunitas mereka, kelompok tersebut membakar seluruh desa hingga rata dengan tanah. Keberhasilan mereka berujung pada pengemasan ulang mereka menjadi RSF pada tahun 2013 oleh Presiden Omar al-Bashir.
Mereka kembali menargetkan komunitas non-Arab di Darfur, yang kini hampir sepenuhnya mereka kendalikan. Namun warga Arab pun mulai mengungsi ke Chad karena krisis kelaparan.
Yassir Hussein, 45, datang ke Adre dari Kamp Ardamata di Darfur Barat, sebuah daerah di mana RSF dan milisi sekutunya membunuh sekitar 1.300 pria Masalit pada Oktober 2023.

“(RSF) tidak menyentuh saya (di Ardamata) karena mereka tahu saya orang Arab dari penampilan dan rambut saya,” kata Yassir kepada Al Jazeera, seraya menambahkan bahwa dia datang ke Chad untuk mencari makanan dan tempat tinggal yang memadai.
Gubernur Adre Mohamad Issa khawatir kedatangan orang Arab Sudan dapat menyebabkan konflik Darfur meluas ke Chad.
Dia menekankan bahwa lebih banyak dukungan kemanusiaan diperlukan untuk semua pengungsi – termasuk komunitas miskin Chad – untuk mengurangi konflik etnis.
“Ada kemungkinan konflik antara Arab dan Masalit akan melintasi perbatasan. Kami sekarang memiliki beberapa pengungsi Arab yang melarikan diri dari kelaparan (di Sudan) dan ini dapat menimbulkan ketegangan,” kata Issa kepada Al Jazeera.
Yassir berharap konflik tidak akan mengikutinya hingga ke Chad. Dia mengatakan dia “tidak punya masalah” dengan Masalit non-Arab dan dia hanya ingin perang dihentikan.
“Tidak ada perbedaan di antara kami,” katanya kepada Al Jazeera. “Kita semua sama di hadapan Tuhan.”
[ad_2]
Sumber: aljazeera.com